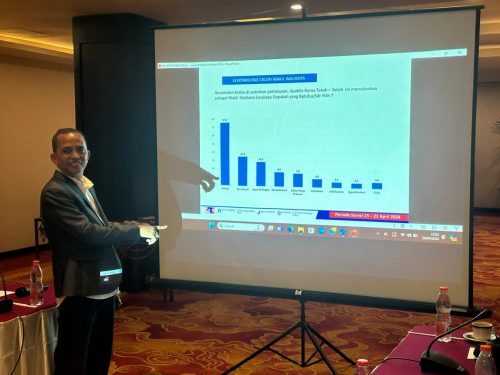Oleh :
Oleh :
Rachmad K Dwi Susilo, Ph.D
Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Lingkungan dan Kebencanaan, Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Public Policy and Social Governance, Hosei University, Tokyo)
PENANDAAN dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Jokowi dan kepala daerah Provinsi, 14 Maret kemarin sejatinya mengingatkan penulis akan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya sumber daya alam. Kita menyaksikan latar ritual Kendi Nusantara dan Kemah Presiden berupa hutan dengan pepohonan menghijau. Tampilan tersebut menjelaskan hutan di Indonesia yang memiliki luas 120,7 juta hektar atau 63,09 persen dari luas daratan (Widyanto, 2020).
Di sini patutlah kita bersyukur sebagai bangsa yang memiliki kekayaan berupa sumber daya hutan yang terbentang di setiap pulau. Banyak keuntungan yang diperoleh dari sumber daya hutan tersebut. Keuntungan tidak hanya ekologis sebagai penyuplai kebutuhan oksigen, tetapi juga memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, bahkan politik. Pemukiman muncul karena masyarakat membuka hutan. Setelah itu, manusia memanfaatkan sumber daya hutan demi berbagai keperluan. Pohon, kayu, plasma nutfah, lahan, binatang dan bahan tambang digali demi kemakmuran manusia. Secara politis, isu asap dan kebakaran hutan kerap menyinggung hubungan diplomatik dan perubahan iklim, maka baik buruknya pemerintah memelihara hutan juga berimplikasi pada relasi dengan negara lain dan dunia internasional. Oleh karena itu secara normatif, hutan harus dipelihara. Pada titik inilah sangat relevan jika komitmen pemeliharaan hutan dikaitkan dengan Peringatan Hari Hutan se-Dunia setiap 21 Maret. Kita memerlukan momen penting untuk evaluasi kondisi hutan hari ini. Kegiatan ini sepatutnya tidak berhenti pada penyadaran, tetapi sampai implementasi, refleksi, evaluasi atas tata kelola perhutanan selama ini.
Akar Persoalan
Secara politis, pemegang kuasa baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat sekitar telah menjadikan hutan sebagai obyek eksploitasi. Hal ini disebabkan paradigma untuk melihat hutan cenderung dari sisi produksi. Para pemangku kepentingan mengambil keuntungan ekonomis dari eksploitasi tersebut. Ironisnya, praktik ini dilakukan sepanjang sejarah. Rezim apapun yang memimpin, hutan tetap dijadikan sebagai pundi-pundi keuntungan.
Pemerintah menarget devisa dari hutan. Para pengusaha melakukan penambangan di wilayah hutan, sedangkan warga sekitar mengambil keuntungan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam sejarah Indonesia mulai Zaman Pra Kolonialisme sampai hari ini hutan terus dieksploitasi. Era Orde Baru, hutan dijadikan sebagai pengundang investor devisa dan komoditas ekspor (Hidayat, 2005). Pemerintah memberi hak pengelolaan hutan kepada pengusaha.
Lemahnya hukum pada transisi Orde Baru ke Orde Reformasi mengakibatkan penjarahan hutan-hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Kemudian, era reformasi memantik pengelolaan hutan berbasis komunitas dimana hari ini kita mengenal perhutanan sosial. Sekalipun demikian, perubahan model ini tidak serta merta berjalan mulus. Dibeberapa kawasan, perhutani tidak begitu saja melepaskan pengelolaan hutan kepada masyarakat. Kemudian, disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 atau dikenal Omnibus Law yang menjadikan hutan sebagai wilayah pertambangan, tidak menghentikan eksploitasi hutan. Begitu dominannnya negara dilihat dari luas kawasan hutan yang didasarkan proyek strategis nasional dan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah.
Konservasi adalah Mitigasi
Sekalipun perhutanan sosial telah meredam konflik kehutanan, tetapi kerusakan hutan sistemik telah menyisakan bencana. Banjir dan tanah longsor sebagai akibat tidak terurusnya hutan terjadi di daerah-daerah seperti Kota Batu, Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Jember, Aceh Utara dan Jayapura.
Memang bencana hidrometereologis merupakan pemicu dengan curah hujan tinggi, tetapi Jika kondisi hutan terawat dengan baik maka setinggi apapun curah hujan, kondisi tetap aman. Oleh karena itu, akar masalah utama disebabkan hutan rusak dan tidak ada pepohonan yang menahan laju banjir dan tanah longsor.
Kerusakan hutan disebabkan penebangan liar, permisifnya pengelolaan tata ruang dan abai pada konservasi hutan. Konservasi berarti memperindah, maka tidak ada batasan jelas. Ekowisata sebagai strategi ekonomi dan ekologi dipersepsi sebagai konservasi, tetapi manakala kegiatan rekreasi lebih banyak dari pada ekologi, sejatinya ia bukan konservasi. Konservasi yang tidak dijelaskan selalu membuka celah untuk abai pada penyelamatan lingkungan sehingga rentan tergelincir dan kembali pada eksploitasi.
Berangkat dari persoalan di atas, kini paradigma pengelolan hutan untuk mitigasi. Mitigasi ini menunjuk segala upaya untuk pengurangan resiko bencana dan jaminan keselamatan warga terutama yang tinggal di sekitar hutan. Mitigasi dilaksanakan baik berbentuk struktural dan non struktural. Mitigasi struktural menjelaskan intervensi fisik seperti pembangunan tempat evaluasi, sedangkan non struktural meliputi pembuatan kebijakan untuk penanggulangan bencana.
Untuk pemeliharaan hutan langkah-langkah penting bisa ditempuh sebagai berikut. Pertama, penegasan negara sebagai ujung tombak mitigasi kehutanan. Wewenang dimiliki Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Perhutani untuk mengelola hutan secara ekologis dan ekonomis. Berangkat dari sini pembagian wilayah dan kewenangan semua stakeholders harus diatur jelas. Secara historis, kegagalan perhutani dalam memberdayakan petani di sekitar hutan harus menjadi pelajaran. Hutan rusak disebabkan petani penyewa “bermotif ekonomi” yang seringkali perhutani permisif dan gagal mengendalikan.
Kedua, memastikan kondisi hutan benar-benar lestari. Secara normatif, setiap kebijakan pasti memasukan monitoring dan evaluasi. Persoalannya, dua langkah ini tidak dilakukan secara maksimal. Seharusnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban, kinerja keduanya dibuka kepada publik. Selama ini negara terlalu “berkuasa” dengan memberi ruang sempit masyarakat lokal untuk mengambil keuntungan dan memelihara dan menjaga hutan-hutan mereka. Akibatnya, warga pun banyak yang tidak tahu kondisi hutan di sekitar mereka. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang pemukiman lepas dari jangkauan warga, mengapa demikian? Negara sering “abai” pada monitoring hutan. Hutan selalu dipantau pasca bencana saja, setelah waktu berjalan, kembali lagi, abai.
Ketiga, perlunya penyegaran mitigasi. Krisis dan kerusakan lingkungan sebagai sasaran utama ditopang oleh perencanaan yang sungguh-sungguh. Penanaman, perawatan dan peanekaragaman pohon harus dilakukan secara cermat. Konservasi hutan tidak hanya hutan jati, tetapi juga hutan-hutan lain seperti Hutan Mangrove. Mempertimbangkan aktor-aktor yang terlibat dalam model pengelolaan dan target mitigasi juga harus mendapatkan prioritas perhatian.
——— *** ——–